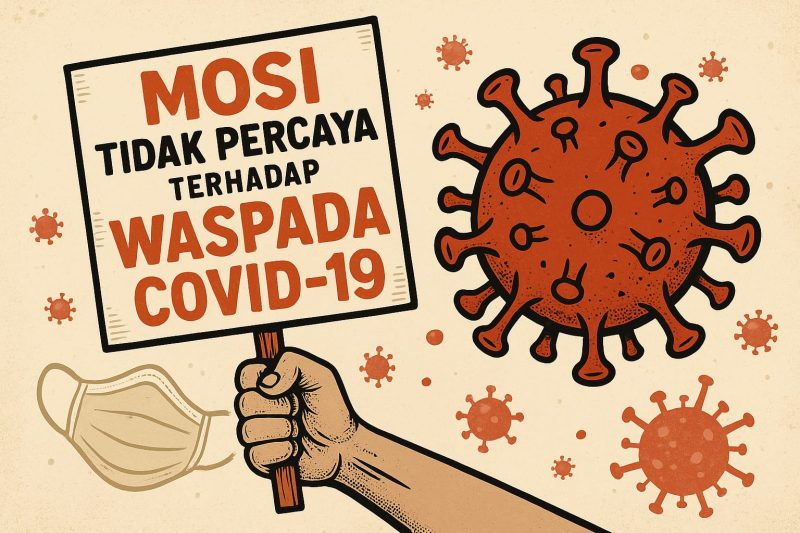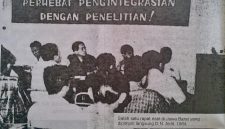Setelah hampir dua tahun berakhirnya pandemi Covid-19 secara resmi melalui Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 yang dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo, masyarakat Indonesia kini kembali dikejutkan dengan “kewaspadaan baru atas peningkatan kasus Covid-19”. Hal itu ditandai dengan surat edaran Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ditetapkan tanggal 23 Mei lalu, yang menekankan perlunya kewaspadaan terhadap peningkatan kasus Covid-19 di tahun ini.
Kendati surat tersebut dikeluarkan oleh lembaga resmi negara, tanggapan masyarakat justru penuh keraguan. Tidak sedikit warga yang mempertanyakan urgensi dari peringatan ini, bahkan menganggapnya sebagai isu yang kembali mengusik stabilitas kehidupan rakyat, bukan dari sisi kesehatan semata, melainkan dari potensi dampak sosial dan ekonomi yang bisa menyertainya. Ingatan masyarakat masih segar akan masa-masa suram tahun 2020 hingga 2021, ketika lockdown diberlakukan secara ketat, menyebabkan gelombang besar pemutusan hubungan kerja, penurunan pendapatan usaha, hingga krisis ketahanan pangan di banyak lapisan sosial.
Sesungguhnya, kekhawatiran masyarakat bukanlah pada virus itu sendiri, melainkan pada kebijakan-kebijakan yang menyertainya yang dianggap tidak berpihak pada keberlangsungan hidup rakyat kecil. Di tengah keterbatasan ekonomi, rakyat lebih takut pada kelaparan daripada penyakit. Mereka takut kehilangan pekerjaan, kehilangan penghasilan, dan kehilangan akses untuk hidup layak, bukan semata-mata karena takut tertular Covid-19.
Sebagai bangsa yang berlandaskan pada Ketuhanan Yang Maha Esa, masyarakat Indonesia memiliki keyakinan spiritual yang kuat. Mereka percaya bahwa hidup dan mati berada di tangan Tuhan, bukan ditentukan oleh pandemi atau kebijakan birokratis. Dalam pandangan mereka, Covid-19 bukanlah penentu takdir, melainkan alat yang dalam dugaan sebagian telah dijadikan sarana politisasi ekonomi. Banyak yang meyakini bahwa pandemi ini telah dijadikan pintu masuk untuk kepentingan industri farmasi global: menjual obat-obatan, alat tes, dan vaksin dalam skala masif dengan pengawasan yang minim dan transparansi yang kabur.
Narasi keraguan terhadap pandemi ini semakin diperkuat oleh pendapat tokoh publik seperti Dharma Pongrekun, seorang purnawirawan Polri yang dikenal kritis terhadap kebijakan pemerintah. Dalam sebuah episode podcast bersama dr. Richard Lee di YouTube, Dharma menyampaikan pandangannya yang kontroversial, bahkan konspiratif, mengenai pandemi global yang dimulai pada 2020.
Menurutnya, pandemi Covid-19 bukanlah peristiwa yang terjadi secara alami, melainkan bagian dari sebuah skenario global yang telah disiapkan jauh sebelumnya. Ia menyebut bahwa rencana ini telah digagas sejak tahun 2010 oleh Rockefeller Foundation, sebuah lembaga filantropi internasional yang sering menjadi sorotan dalam teori-teori konspirasi. Dharma mengutip salah satu dokumen skenario dari lembaga tersebut, yang menggambarkan simulasi respon pemerintah terhadap suatu pandemi sebagai semacam cetak biru dari peristiwa yang akhirnya benar-benar terjadi satu dekade kemudian.
Lebih jauh, ia menafsirkan ulang akronim Covid-19 dengan makna yang sepenuhnya berbeda dari definisi resmi. Bagi Dharma, Covid bukanlah singkatan dari Corona Virus Disease 2019, melainkan [C]ertificate [O]f [V]accine [ID]entification. Ia menyatakan bahwa Covid adalah kode bagi proyek digitalisasi global yakni sistem identitas digital berbasis vaksin yang disiapkan untuk mengawasi populasi dunia. Ia juga menafsirkan angka “19” sebagai simbol tersembunyi: angka 1 mewakili huruf “A” (Artificial), dan angka 9 sebagai huruf “I” (Intelligence), yang jika digabung membentuk “AI” (Artificial Intelligence).
Dari tafsir itu, ia menyimpulkan bahwa pandemi ini hanyalah langkah awal menuju dunia yang dikendalikan oleh sistem kecerdasan buatan. Di balik protokol kesehatan, vaksinasi massal, dan sertifikat digital, ia melihat struktur kontrol yang rapi, yang perlahan-lahan merampas hak asasi dan kebebasan manusia. Dalam narasinya, Covid-19 bukan semata penyakit, melainkan alat rekayasa sosial menuju peradaban yang sepenuhnya dikuasai oleh teknologi, sistem, dan kekuatan global yang tidak bertanggung jawab secara demokratis.
∗ ∗ ∗
Setelah melewati badai pandemi dan mencicipi pahitnya kebijakan yang membatasi ruang hidup, kini publik kembali dihadapkan pada narasi yang serupa: kewaspadaan. Namun kali ini, masyarakat tak lagi berdiri di tempat yang sama. Mereka telah belajar, menyimpan ingatan, dan membentuk daya kritis atas apa yang pernah terjadi.
Mosi tidak percaya yang berkembang bukan tanpa alasan. Ia lahir dari luka kolektif, dari trauma sosial yang tak diobati, dari kebijakan yang pernah menekan tanpa logika yang transparan. Dan ketika suara-suara resmi kembali datang membawa peringatan, wajar bila publik tak langsung bersimpuh percaya. Karena kepercayaan yang dulu dirusak tidak bisa dibangun kembali hanya dengan surat edaran.
Yang dipertaruhkan bukan sekadar kebijakan kesehatan, melainkan masa depan nalar publik. Jika pemerintah terus memilih jalan satu arah mengatur tanpa dialog, memutuskan tanpa mendengar, maka jurang ketidakpercayaan akan makin dalam. Kita tidak bisa terus-menerus diminta takut, lalu patuh, tanpa diberi ruang untuk bertanya.
Hari ini, yang dibutuhkan bukan sekadar imbauan waspada, tapi juga keberanian untuk membuka data, menjelaskan motif, dan melibatkan publik dalam proses berpikir. Tanpa itu semua, peringatan hanya akan terdengar seperti gema dari masa lalu yang tak lagi punya tempat di telinga yang telah lelah.
Karena pada akhirnya, rakyat bukan mesin yang bisa dikendalikan dengan tombol darurat. Mereka adalah manusia dengan memori, intuisi, dan akal sehat. Dan jika akal sehat itu berkata: “cukup sudah,” maka mosi tidak percaya bukan sekadar pernyataan, melainkan bentuk pertahanan terakhir terhadap kewarasan bersama.
Artikel Lain :
Resensi Buku: Seni Mencintai – Erich Fromm
Ketergantungan Negara terhadap Investasi Asing
Negara dalam Proyek Politik Neo-Liberalisme
Penulis : Boy Dowi
Editor : Redaktur