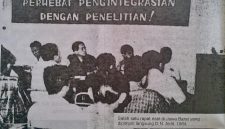Ketahanan pangan merupakan isu serius internasional saat ini, tentunya bagi Indonesia juga. Sebagai aspek dasar penopang kehidupan suatu negara yang mana “pembangunan dapat laju berjalan” setelah terpenuhinya aspek ketahanan pangan negara tersebut.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, ketahanan pangan merupakan kondisi “terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan” tercermit dari ketercukupan, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau. Lalu seturut dengan aspek lain, seperti agama, keyakinan dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
Menyoroti hal tersebut, maka tentunya petani merupakan garda pertama dan terdepan dalam proses produksi pangan, dan kondisi mereka sering kali mencerminkan sejauh mana ketahanan pangan suatu negara dapat bertahan.
Menurut catatan Badan Pusat Statistik (BPS) yang penulis lansir dari Indonesia.go.id, bahwa produksi beras Indonesia pada periode Januari-Maret 2025 mencapai 8,67 juta ton, mengalami lonjakan tajam sebesar 52,32 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2024 yang hanya tercatat 5,69 juta ton.
Potensi peningkatan produksi beras ini sejalan dengan meluasnya potensi luas panen padi yang diperkirakan mencapai 2,83 juta hektare. Angka ini menunjukkan kenaikan sekitar 970,33 ribu hektare atau 52,08 persen dibandingkan dengan luas panen pada Januari–Maret 2024 yang hanya sebesar 1,86 juta hektare.
Membuktikan unsur krusial ketahanan pangan adalah “petani” — yang justru mengalami banyak hambatan. Seperti yang disampaikan oleh Suhaenah, yang hanya berdasarkan pengetahuan tradisional, ia mengemukakan bahwa perubahan iklim dan cuaca menjadi salah satu tantangan utama dalam pertanian.
Musim ekstrim yang berubah-ubah membuat padi kosong tanpa isi, sehingga hasil tani menjadi tidak maksimal dan panen “tergantung, kadang bagus, kadang juga kosong alias gebug, ya tergantung cuacanya,” ungkap Suhaenah, petani asal Desa Wanakarta, Serang (22/2).
Kesulitan pupuk juga menjadi hambatan, sebab sebelumnya para petani membeli pupuk pada langganan dengan harga yang relatif terjangkau, sekarang “sulit dapetin pupuknya, harus pesan dulu pupuknya ke penjual pupuk, dan banyak petani yang udah pesen dulu.
“Jadinya susah buat dapetinnya, dan emang harus pesen dari jauh hari. Harganya juga lumayan mahal, sekitar Rp. 165.000,00 / karung, belum lagi harus beli obat keong, kalo lagi banyak keong bisa sampe lima kali,” jelas Suhaenah, lansia berumur 60 yang harus juga berfikir cara membeli obat hama bagi sawahnya.
Selanjutnya, akses untuk mengairi lahan pertanian menjadi hambatan paling sulit. Sumber air yang jauh makin menguras tenaga para pejuang ketahanan pangan. Menurut Suhaenah, teknologi informasi menjadikan pemerintah tidak “mendapat pemberitahuan [atau informasi] yang cukup” untuk sekedar meningkatkan pendapatan dan menjaga kestabilan harga.
Dalam sektor pertanian, air merupakan salah satu komponen utama. Namun, air juga bisa menjadi hambatan, sebab sulitnya mengakses air guna mengairi lahan pertaniannya bagi petani dikarenakan jarak tempuh yang cukup jauh sehingga harus mengeluarkan tenaga lebih banyak dan waktu yang relatif lebih lama.
Akhirnya setiap hambatan tersebut membuat petani berharap agar kebijakan pemerintah dapat lebih mendukung kesejahteraan mereka. Program bantuan subsidi yang lebih mudah didapatkan, pemberian modal yang fleksibel, kemudahan atas akses air guna pertanian, teknologi terbarukan, serta penyuluhan yang lebih intensif akan sangat membantu dalam mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi.
Selain itu, penting bagi petani untuk mendapatkan jaminan harga yang lebih stabil, terlebih pupuk dan bibit dengan kualitas baik dan harga relatif terjangkau menjadi peran krusial dalam pertanian. Sehingga, prinsip serta upaya dalam ketahanan pangan mudah dijalankan khususnya di Indonesia.
Artikel Lain: Reforma Agraria dan Proyek Strategis Nasional
Penulis : Dwi Lestari
Editor : Alda