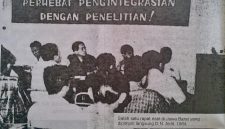Sebagai negara agraris Indonesia dianugrahi kekayaaan hayati yang luar biasa. Namun, di balik potensi besar itu, krisis ketahanan pangan terus mengintai. Ketergantungan terhadap beberapa komoditas utama seperti beras, jagung, dan gandum menempatkan negeri ini dalam posisi rentan terhadap guncangan global.
Kemiskinan pedesaan di Indonesia telah lama menjadi paradoks yang membayangi geliat pembangunan nasional. Ironisnya masih banyak keluarga yang hidup di bawah garis kemiskinan. Seperti diungkapkan Robert Chambers dalam Rural Development: Putting the Last First (1983), penyebab stagnasi pembangunan desa sering kali bukan pada kemiskinan sumber daya, melainkan pada kegagalan untuk memberdayakan masyarakat lokal agar menyadari dan mengembangkan potensi yang mereka miliki.
Berangkat dari hal tersebut, hadirlah inovasi integratif berbasis sorgum menawarkan jawaban konkret dan visioner: memperkokoh ketahanan pangan Nusantara dengan kembali kepada kearifan lokal yang dikembangkan secara modern. Sorgum (Sorghum bicolor), tanaman serbaguna asli Afrika yang telah lama beradaptasi di tanah Nusantara, membawa potensi strategis yang selama ini terabaikan.
Ketahanannya terhadap iklim kering, kebutuhan air yang rendah, serta kandungan gizi yang tinggi menjadikannya alternatif ideal untuk diversifikasi pangan nasional. Sayangnya, sorgum masih dipandang sebagai tanaman “kelas dua”, tersisih oleh dominasi padi dan jagung. Disinilah urgensi inovasi integratif: mempertemukan pengetahuan tradisional dengan teknologi modern, menghubungkan petani, peneliti, pengusaha, dan pembuat kebijakan dalam satu ekosistem pembangunan pangan.
Dalam konteks ini, Value Chain (Gereffi, 1999) memberikan sebuah pandangan sebuah negara berkembang akan mendapatkan manfaat maksimal bukan dari mengekspor bahan baku, tetapi dari menguasai rantai nilai pengolahan. Jika Indonesia ingin membangun ketahanan pangan sejati, maka harus berpikir dari “biji ke roti”, bukan dari “biji ke pasar”. Artinya, dari produksi hingga konsumsi, seluruh rantai ekonomi sorgum harus terintegrasi.
Pendekatan inovatif terhadap sorgum harus dimulai dari inkulturasi budaya pangan. Sorgum harus direstorasi bukan sekadar sebagai pengganti darurat, melainkan sebagai bagian dari identitas kuliner bangsa. Selanjutnya, inovasi budidaya berbasis teknologi tepat guna harus diakselerasi. Pengembangan varietas unggul lokal, penerapan sistem tanam tumpangsari sorgum dengan tanaman hortikultura, serta pemanfaatan pertanian presisi akan meningkatkan produktivitas tanpa membebani ekosistem.
Di sisi industrialisasi sebagai bahan baku bioetanol, pakan ternak berkualitas, hingga produk farmasi dan kosmetik, membuka peluang besar bagi ekonomi berbasis pertanian berkelanjutan. Instrumen geopolitik pangan Nusantara. Dalam dunia yang dilanda perubahan iklim, peperangan, dan ketidakpastian rantai pasok, kemandirian pangan berbasis tanaman lokal menjadi kartu truf strategis. Indonesia memiliki peluang emas untuk tidak hanya memenuhi kebutuhan domestik, tetapi juga menjadi eksportir sorgum global, mengukuhkan posisi dalam peta pangan dunia.
Dukungan terhadap Petani Sorgum
Ketahanan pangan nasional tidak sekadar soal memenuhi stok beras. Ia adalah soal kemandirian sebuah bangsa untuk mengelola kekayaan hayatinya sendiri. Dalam dunia yang kian tak pasti, Indonesia harus berani melirik sumber daya alternatif: tanaman lokal yang tahan banting, bergizi tinggi, dan serba guna. Salah satunya adalah sorgum.
Namun, peluang itu hanya akan menjadi kenyataan jika negara hadir memberikan dukungan nyata, mulai dari insentif produksi di tingkat hulu hingga hilirisasi industri di tingkat hilir. Insentif produksi adalah fondasi. Pemerintah perlu hadir melalui, subsidi benih dan pupuk: Penyediaan varietas unggul sorgum yang adaptif terhadap berbagai iklim Nusantara. Pendanaan Mikro dan Kredit Khusus dalam membuka akses permodalan murah untuk petani sorgum. Pelatihan dan Penyuluhan yang memberikan transfer teknologi tentang teknik budidaya modern dan pengolahan sorgum. Skema Harga Minimum menjamin harga dasar sorgum di tingkat petani agar mereka terlindung dari fluktuasi pasar.
Sebagaimana disebutkan dalam konsep Agricultural Development oleh Hayami dan Ruttan (1971), insentif harga dan teknologi adalah dua pilar yang harus sejalan untuk mendorong produktivitas pertanian. Tanpa jaminan insentif ekonomi, petani tidak akan berminat mengadopsi inovasi baru. Seperti ditulis oleh Michael Porter dalam Competitive Advantage (1985), keunggulan suatu sektor tidak lahir dari potensi alam semata, melainkan dari kemampuan menciptakan sistem produksi dan distribusi yang efisien dan inovatif. Prinsip ini harus menjadi dasar dalam pengembangan sorgum nasional.
Tentu, perjalanan inovasi integratif sorgum tidak akan mudah. Ia menuntut kolaborasi lintas sektor, visi jangka panjang, serta keberanian untuk keluar dari bayang-bayang ketergantungan historis pada beras dan gandum. Sebagaimana sejarah membuktikan bahwa kekuatan sebuah peradaban terletak pada kemampuannya mengelola sumber dayanya, masa depan ketahanan pangan Indonesia sangat mungkin diselamatkan oleh tanaman sederhana. Namun, kesederhanaan itu harus dibungkus dengan inovasi, diperkuat dengan kolaborasi, dan digerakkan oleh tekad nasionalisme.
Artikel Lain : Stunting di Tengah Surplus Panen jadi Ironi Pandeglang
Penulis : Moh. Hairud Tijani
Editor : Alda