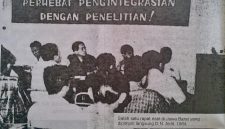PENAMARA.id — Agama, kuasa, dan tubuh yang dibungkam adalah pemilihan kata yang dapat mengambarkan momok menyeramkan bernama kekerasan seksual yang terjadi di pesantren. Beberapa waktu terakhir, Menteri Agama menyebutkan bahwa pemberitaan tentang kekerasan seksual di pesantren terlalu “dilebih-lebihkan” oleh media. Pernyataan ini menuai reaksi keras dari publik, terutama dari aktivis perempuan dan kelompok masyarakat sipil. Tuduhan “berlebihan” itu menunjukkan betapa biasnya cara pandang Menteri Agama, Nasarudin Umar, lewat perwakilan lembaga negara dalam memahami kekerasan seksual. Pemaknaan terhadap kekerasan seksual bukan sebagai persoalan kemanusiaan merupakan ancaman terhadap citra lembaga negara.
Data menunjukkan fakta yang sebaliknya. Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat ada 573 kasus kekerasan di sekolah dan pesantren sepanjang 2024, dimana angka tersebut meningkat 100% dari tahun sebelumnya. Data tersebut menunjukan bahwa 20% kasus kekerasan di sekolah terjadi di lingkungan pesantren. Cara pandang interseksional oleh Kimberlé Crenshaw menekankan bahwa penindasan itu tidak berdiri tunggal. Kekerasan seksual di pesantren tidak hanya berakar pada isu gender tetapi juga pada relasi kuasa, kelas sosial, usia, dan status religius.
Ketika pelecehan atau kekerasan terjadi, para santri harus berhadapan dengan lapisan hambatan seperti hierarki spiritual, budaya patriarki, dan rasa takut yang dianggap akan melawan ajaran agama. Inilah yang disebut sebagai penindasan yang saling tumpang tindih.
Dalam banyak kasus kekerasan seksual tidak muncul karena “nafsu semata”, tetapi karena ketimpangan kuasa yang dilegitimasi agama. Sering kali otoritas pimpinan atau guru dianggap suci dan tak bisa dikritik. Relasi guru dengan santri diidealkan sebagai bentuk kepatuhan “ta’dzim” yang dalam praktiknya sering kali bias antara batas penghormatan dan kekerasan. Ketika agama dipakai untuk membungkus kekerasan, maka tubuh korban tak hanya dilukai secara fisik, tetapi juga secara spiritual.
Penelitian Cakra Wikara Indonesia (2023) menemukan bahwa banyak kekerasan seksual di pesantren justru disamarkan sebagai “bimbingan” atau “latihan kesabaran”. Ada santri yang diminta memijat Kiai/Kyai di malam hari, atau dipanggil ke kamar pengasuh dengan dalih konsultasi rohani. Ketika menolak mereka dituduh tidak patuh, tetapi ketika melapor mereka diancam dikeluarkan.
Kondisi ini menunjukkan bahwa agama bisa menjadi ruang ambivalen yang dimana satu sisi menawarkan nilai moral, tapi di sisi lain menjadi tameng bagi kekerasan yang bersifat struktural. Seperti yang dikatakan teolog feminis Riffat Hassan, agama sering ditafsirkan secara patriarkal yang kerapkali menempatkan perempuan bukan sebagai subjek spiritual tetapi objek moral yang harus dijaga, diawasi, bahkan dikontrol.
Relasi kuasa di pesantren memperkuat budaya diam dimana korban sulit bersuara karena pelaku adalah figur yang cukup dihormati. Komunitas cenderung melindungi institusi ketimbang korban. Bahkan “Aib pesantren” dianggap lebih berbahaya daripada trauma santri. Dalam situasi ini, pelaporan kasus bukan hanya soal keberanian individu, tetapi juga perlawanan terhadap sistem sosial dan religius yang melindungi pelaku.
Data dari Komnas Perempuan (2024) menunjukkan, sepanjang 2023–2024, lebih dari 3.000 kasus kekerasan seksual terjadi di ruang pendidikan dan keagamaan, namun hanya sebagian kecil yang masuk ke pengadilan. Banyak korban menarik laporan karena tekanan sosial dan ancaman dari pihak pesantren. Pendekatan interseksional membantu kita memahami mengapa yang menjadi korban selalu perempuan, terutama dari kelas ekonomi bawah. Mereka tidak hanya menghadapi pelaku dan lembaga tetapi juga stigma masyarakat yang menganggap perempuan “mengundang dosa”.
Ketika pejabat publik mengatakan bahwa kasus seperti ini dilebih-lebihkan, sesungguhnya mereka melakukan kekerasan simbolik. Pernyataan semacam itu menghapus penderitaan korban dan menormalisasi kekerasan. Pernyataan tersebut juga menegaskan bagaimana negara lebih sibuk menjaga reputasi lembaga agama ketimbang memastikan keadilan.
Kita perlu mengingat bahwa mengakui kekerasan bukan berarti menyerang agama, melainkan menyelamatkan nilai-nilai spiritual yang sejatinya keadilan, kasih sayang, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Kita harus menafsir ulang relasi kuasa dalam lembaga keagamaan agar lebih manusiawi dan egaliter.
Melindungi pesantren bukan berarti menutup mata terhadap kekerasan, tetapi justru membuka ruang pertanggungjawaban. Kita perlu berani menantang tafsir yang membenarkan ketimpangan, karena agama sejatinya bukan alat untuk berkuasa, melainkan jalan pembebasan. Mengakui bahwa kekerasan seksual memang nyata, sistemik, dan melibatkan relasi kuasa adalah langkah pertama menuju penyembuhan kolektif.
Baca lagi soal Kekerasan Seksual: Perempuan, 1965, dan Luka yang Membekas
Penulis : Agsel Jesisca
Editor : Redaktur