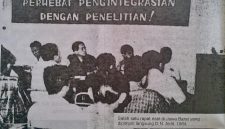PENAMARA.id — Perempuan, 1965, dan luka yang membekas menjadi bayangan atas cerita tentang peristiwa politik yang besar seperti perebutan kekuasaan, tentara, partai, dan propaganda. Namun, jarang sekali kita telisik lebih dalam bagaimana dampaknya terhadap kelompok masyarakat yang seringkali terpinggirkan terutama perempuan. Padahal, perempuan seringkali banyak menanggung beban, baik sebagai korban langsung maupun lewat stigma panjang yang diwariskan sampai ke anak cucunya.
Kita mungkin sering mendengar nama “Gerwani” yang disebut-sebut sebagai biang kerok dari rentetan peristiwa yang terjadi pada tahun 1965. Propaganda Orde Baru dengan sengaja membangun narasi perempuan Gerwani adalah kelompok perempuan yang kejam, cabul, dan biadab. Padahal banyak penelitian yang menunjukkan bahwa cerita tersebut adalah hasil dari manipulasi kekuasaan Orde Baru untuk menghalau gerakan kiri di Indonesia.
Komnas Perempuan mencatat bahwa perempuan mengalami kekerasan seksual, penyiksaan, dan diskriminasi berlapis akibat stigma politik yang dilekatkan pada mereka, dan itu dilakukan secara sistematis serta dibiarkan begitu saja oleh negara (Komnas Perempuan, 2012). Narasi manipulatif dan tipu daya itu sangat sukses membuat posisi perempuan semakin menjadi sasaran kekerasan yang jauh lebih brutal.
Mari kita bayangkan. Satu sisi, stigma itu lahir dari institusi besar bernama negara dan ditambah lagi oleh masyarakat yang kemudian mengamini serta hidup di dalam manipulasi kekuasaan. Perempuan yang pernah bersentuhan dengan organisasi kiri atau bahkan yang “dituduh” pun bisa kehilangan hidupnya. Ada yang ditahan bertahun-tahun tanpa proses hukum, ada yang anak-anaknya ikut dikucilkan di sekolah, ada yang tidak dapat akses terhadap pekerjaan hanya karena identitas keluarganya.
KontraS mencatat, kekerasan pasca 30 September 1965 termasuk penahanan yang sangat sewenang-wenang, pembunuhan massal, penyiksaan, dan diskriminasi berkepanjangan. Korban perempuan mendapat perlakuan paling kejam, tapi ceritanya jarang diakui (KontraS).
Kalau kita tarik kedalam perspektif feminis, jelas ini semua bukan hanya soal politik, tetapi juga soal tubuh perempuan yang dijadikan medan perang. Kekerasan seksual jadi alat untuk mempermalukan, menghancurkan, dan membuat trauma berkepanjangan bahkan sampai seumur hidup. Dan yang paling ironis adalah, cerita pengalaman penyintas seringkali dibungkam.
Human Rights Watch bahkan mencatat, selain ratusan ribu orang tewas, perempuan menghadapi kekerasan seksual serta stigma sosial yang diwariskan ke anak cucu mereka (HRW, 2016). Jadi perempuan nggak cuma kehilangan haknya sebagai warga negara, tapi juga direbut suaranya sebagai manusia. Dari segi sosial, bebannya pun berlapis. Perempuan yang menjadi korban tetap harus bertahan hidup, mengurus anak, kerja serabutan, sambil menghadapi tatapan penuh kecurigaan serta intimidatif dari masyarakat.
Kita bayangkan, pagi-pagi mereka harus memutar otak mereka untuk memberi makan keluarga, tapi malamnya dihantui rasa takut entah kapan aparat datang lagi. Banyak kisah perempuan dipaksa jadi tulang punggung keluarga karena suaminya ditahan atau dibunuh. Jadi ya, mereka bukan cuma korban, tapi juga penopang kehidupan yang dipaksa kuat di tengah stigma.
Dan luka itu masih hidup sampai hari ini. Anak-anak dari korban perempuan 1965 masih sering dicap buruk sebagai “turunan PKI“. Bayangkan, dosa politik yang mereka tanggung sebenarnya tidak pernah mereka pilih dan ini selalu diturunkan begitu aja. Anak perempuan justru akan lebih berat karena mereka bukan hanya harus survive dari diskriminasi sosial, tetapi juga dari ekspektasi gender yang timpang sejak awal.
Kenapa penting kita angkat perspektif feminis di sini?
Sejarah seringkali ditulis dari kacamata laki-laki. Sejarah 1965 selalu dilihat sebagai konflik tentara, elite politik, atau perebutan kursi kekuasaan. Padahal, di tingkat paling bawah, yang paling menderita justru perempuan. Tubuhnya dihancurkan, suaranya dibungkam, dan ceritanya selalu dipelintir untuk kepentingan propaganda. Dengan perspektif feminis, kita bisa patahkan cara pandang itu: dari sekadar narasi besar negara ke cerita-cerita kecil yang justru membongkar wajah asli kekerasan negara terhadap perempuan.
Sekarang, lebih dari setengah abad berlalu, luka itu belum juga sembuh. Banyak korban perempuan sudah meninggal tanpa pernah dapat pengakuan atau keadilan. Anak-anak mereka masih hidup dengan trauma sosial. Amnesty International mencatat, meski sudah lebih dari 50 tahun, korban dan keluarga masih menunggu pengakuan, keadilan, dan pemulihan. Pemerintah berulang kali berjanji manis, tetapi belum pernah ada langkah nyata (Amnesty, 2016). Sementara itu, negara masih gagap, kadang pura-pura lupa, dan juga kadang malah ikut aktif membungkam diskusi.
Tetapi buat saya, mengingat peristiwa kelam yang terjadi pada tahun 1965 ini bukan hanya sekadar soal politik masa lalu. Mengingat 1965, apalagi dari kacamata feminis, adalah cara kita berefleksi diri: jangan sampai tubuh perempuan selalu menjadi korban atas nama kekuasaan. Jangan sampai sejarah ini pada akhirnya hanya dijadikan alat propaganda tanpa pernah mendengar suara mereka yang paling menderita.
Karena pada akhirnya kalau kita hanya diam, berarti kita ikut juga melanggengkan stigma itu. Kalau kita tidak mau mendengar suara perempuan korban, berarti kita lebih percaya propaganda daripada kenyataan. Dan kalau itu terus terjadi, berarti kita semua masih hidup dalam warisan Orde Baru yang membuat kita lupa siapa sebenarnya yang paling banyak dirugikan tidak lain adalah perempuan yang selalu dibungkam dan dibunuh karakternya.
Mengingat 1965 bukan cuma soal melawan lupa tapi juga soal menolak diam di hadapan ketidakadilan. Dan buat saya, perspektif feminis adalah pintu yang paling jujur untuk melihat luka itu. Karena lewat feminisme, kita bisa paham bahwa yang dipertaruhkan bukan cuma politik negara, tapi juga martabat perempuan, kehidupan sehari-hari mereka, dan hak mereka untuk hidup tanpa stigma.
Baca lagi: Nirempati Fadli Zon terhadap Kasus Pemerkosaan Massal Mei ’98
Penulis : Agsel Jesisca
Editor : Agnes Monica